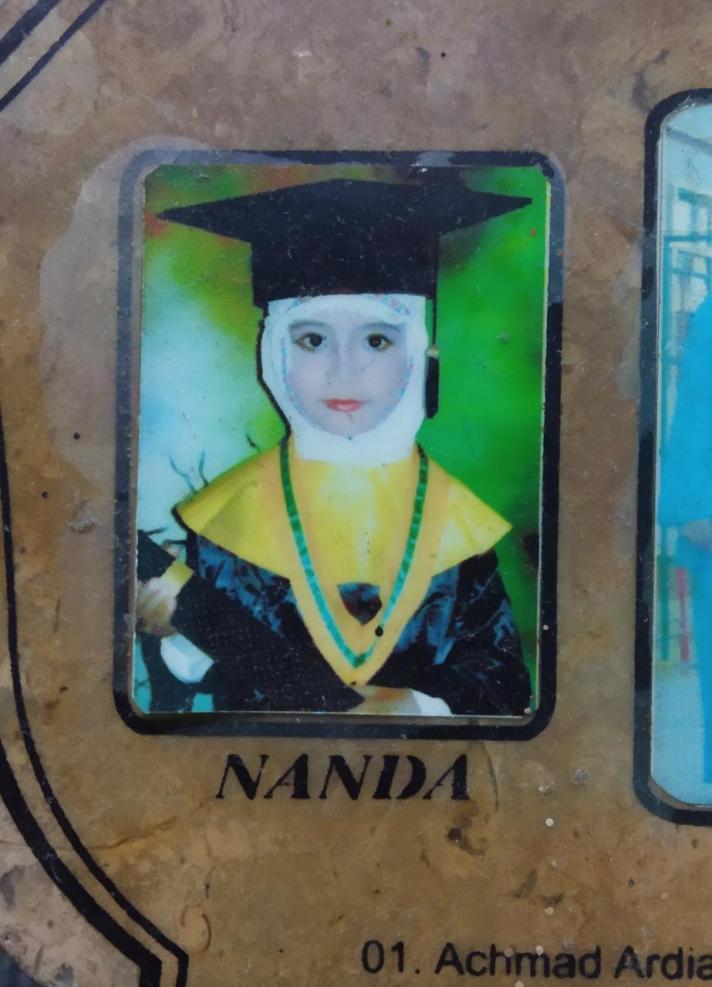Perempuan kecil itu duduk di sisi kanan kelas, tidak terlalu di belakang, tidak terlalu di depan. Kelas itu nampak sedikit berbeda dengan adanya panggung seukuran kira-kira 2,5×3 meter di depan, yang sesungguhnya hanyalah susunan meja yang ditutup karpet.
Berhari-hari sebelumnya, ia sudah tekun berlatih dengan seorang ustadzah. Sehingga, harusnya, mantaplah ia untuk tampil hari ini.
Dipegangnya naskah puisi yang akan membawanya ke atas panggung nanti. Satu per satu anak lain seusianya dipanggil namanya. Mereka tampil bergantian. Perempuan kecil itu mulai nervous: ini pertama kalinya ia akan membacakan sebuah puisi di depan orang-orang. Hingga akhirnya namanya dipanggil…
Ia berjalan dengan kaki yang terasa kaku. Naik ke atas panggung dan berdiri tepat di tengahnya. Nampaklah seisi ruangan, dari sudut ke sudut. Begitu jelas di hadapannya peserta baca puisi lain sedang duduk di kursi-kursi yang tersusun rapi. Semua mata tertuju pada si perempuan kecil. Dirasakan wajahnya memerah, panas dingin. Ia mengangkat naskah puisinya. Naskah yang seharusnya diangkat cukup setinggi dada, malah kelewat naik sampai menutup wajah—ia tak ingin melihat penonton, tak berani menatap. Perempuan kecil itu mulai membaca puisi. Suaranya bergetar. Seluruh latihan—intonasi, gestur, ekspresi—yang dipelajari tiba-tiba plung, jatuh dan hilang. Bisa baca sampai selesai dan turun panggung sendiri saja sudah Alhamdulillah.
***
Perempuan kecil itu aku wkwk. Memori itu adalah ketika aku ikut lomba baca puisi di TK, pertama kali baca puisi di depan orang banyak. Agak samar ingatanku tentang keseluruhan cerita itu, tentang bagaimana aku bisa ikut, siapa yang mengajariku, tapi teringat jelas, masih sangat jelas sampai sekarang betapa perasaan gugup di atas panggung itu betul-betul meluap. Tujuh tahun setelah kejadian itu, kelas VII SMP aku dan dua orang teman—yang lebih akrab dengan dunia baca puisi—sempat ikut lomba baca puisi yang diadakan di sebuah universitas swasta di kota. Di lomba kedua ini, setidaknya aku sudah berani menatap penonton dan memainkan posisi naskah puisi yang dipegang—tidak lagi menjadi robot baca puisi. Tapi ya nggak menang wkwk. Gak banyak berharap juga. Emang karena pengen ikut aja, penasaran.
Aku ingat pengalaman ini setelah sejak beberapa bulan lalu tiba-tiba kangen baca puisi. Sebenernya aku bukan pembaca puisi ulung—yaa kebaca lah ya dari dua pengalaman di atas, sama sekali gak menampakkan kemahiran. Tapi cukup suka. Terakhir kali baca puisi di depan orang banyak adalah ketika kelas XII, saat pelajaran bahasa Madura. Materinya membuat puisi bahasa Madura, lalu membacakannya di depan kelas. Setelah itu, gak pernah lagi.
Apakah sampai tulisan ini ditulis aku masih ingin baca puisi? Iya. Malah sempet kepikiran bikin video baca puisi untuk selanjutnya diupload di salah satu media sosial. Tapi masih mengumpulkan kepercayaan diri wkwk.
Kalau ada pertanyaan dari mana asal-muasal kesukaan baca puisi ini muncul, mungkin secara gak sadar jawabannya adalah dari ayahku. Ternyata, ayahku adalah seorang pembaca puisi yang—menurut pengakuannya sendiri—cukup hebat pada masanya. Katanya, dulu ayahku pernah ikut lomba baca puisi sampai masuk ke tingkat provinsi. Walaupun sampai saat ini aku sama sekali gak pernah ngeliat beliau baca puisi dengan serius. Mungkin itu salah satu perwujudan “buah tak jatuh jauh dari pohonnya” yang diturunkan ke aku—bedanya, aku sendiri belum pernah mencatatkan prestasi apa-apa di dunia baca puisi.